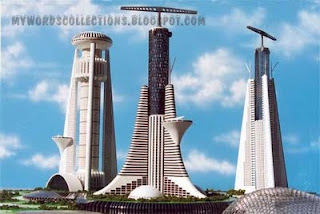Oleh: Mendiola B Wiryawan
Dalam musim kampanye pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lalu, saya sempat menyaksikan sebuah presentasi program cawapres di salah satu televisi swasta. Dalam sesi tanya jawab yg digelar, salah seorang audience bertanya tentang konsep cawapres mengenai kebijakan kebudayaan nasional. Dia mengawalinya demikian. “Anak-anak sekarang sudah melupakan kebudayaan kita sendiri, contohnya mereka banyak yang tidak tahu cerita Sri Rama, (Shinta),… (dst, dst)”. Setelah mendengar pertanyaan tadi, tiba-tiba saja pertanyaan-pertanyaan kebudayaan menghinggapi kepala saya. Apakah benar Rama adalah kebudayaan Indonesia? Apakah karena sering hadir dalam cerita perwayangan Jawa, Sunda, dan beberapa kebudayaan lokal lainnya selama berabad-abad lantas kita dapat meng ‘claim’ nya sebagai budaya Indonesia? (Seperti kita ketahui, Rama dan Shinta berasal dari mitologi kebudayaan Hindu India). Jika begitu apakah Malaysia boleh meng ‘claim’ reog yang katanya milik sebuah daerah di negeri Jiran itu meskipun aslinya dari Ponorogo? Apakah sesuatu yang sudah turun temurun kita dengar atau gunakan lantas otomatis menjadi milik kita? Apakah seorang anak suku Dani di Papua harus mengetahui cerita Rama Shinta (Ramayana) yg mungkin tidak pernah diperkenalkan oleh orangtuanya? Apakah saya yang suka pakai celana jeans bukan orang Indonesia? Apakah yang menjadi budaya bangsa harus orisinal? Bukan berasal dari luar negeri? Apakah yang orisinal?
Semua pertanyaan tadi akhirnya bermuara pada sebuah pertanyaan besar: apakah budaya Indonesia itu? Pertanyaan ini memang sebuah pertanyaan abadi apalagi untuk seorang insan kreatif.
Kata budaya memang merupakan kata yg sangat kompleks pengertiannya. Menurut seorang pengamat dan kritikus kebudayaan, Raymond Williams, kebudayaan (culture) merupakan salah satu dari dua atau tiga kata yang paling kompleks penggunaannya. Di Indonesia, budaya paling sering diartikan sempit pada bentuk kegiatan intelektual artistik dengan produk-produknya yang telah dialihkan turun temurun (heritage). Manifestasinya paling umum adalah segala bentuk kesenian tradisional. Karenanya kalau kita mendengar kata Pameran Budaya Indonesia kita sudah pasti dapat menebak isinya (kerajinan, tari-tarian tradisional, dsb). Padahal budaya dapat dilihat dari berbagai sisi yang lain, misalnya budaya sebagai totalitas gaya hidup, budaya sebagai pola pemecahan masalah hidup, dsb. (Menurut antropolog Kroeber dan Kluckhohn ada enam pemahaman pokok terhadap kata budaya yang saya tidak bahas satu persatu dalam tulisan ini).
Dalam tulisan ini saya hanya akan menyoroti identitas sebagai salah satu ‘pisau bedah’ sudut pandang budaya. Dari kasus penanya cawapres di atas, menurut saya sebenarnya poin utama si penanya adalah, bagaimana kalau si generasi penerus tidak mempunyai identitas yang ‘sama’ seperti identitas yang saya anut selama ini? Bagaimana kalau generasi penerus tidak punya identitas yang selama ini ‘saya anggap’ khas Indonesia dan menjadi manusia global yang tanpa identitas khas?
Persoalan identitas akan selalu menarik. Identitas adalah sebuah pertanyaan dasar dari setiap manusia. Kita tumbuh dan berkembang dalam mencari identitas. Masa remaja sering dianggap masa pencarian identitas manusia. Pada kenyataannya seumur hidup kita adalah sebuah proses berjalan pembentukan identitas. Orang tua dan lingkungan sekitar kita berperan sangat besar dalam menentukan identitas kita. Uniknya identitas pun kadang-kadang bukan persoalan hitam putih ataupun sesuatu yang utuh. Saya ambil analogi sebagai berikut: Ketika Persib Bandung melawan Persija Jakarta, identitas para suporter terbagi menjadi: “Lu anak Bandung, gue anak Jakarta”. Selanjutnya ketika tim sepakbola Indonesia melawan Korea, identitas suporter berubah menjadi “Kita orang Indonesia dan mereka orang Korea” (padahal mungkin para suporter Indonesia terdiri dari suporter Persib dan Persija yang sebelumnya berseteru sampai ada korban nyawa). Disinilah terlihat identitas bukanlah sesuatu yang solid. Identitas menjadi begitu dinamis ketika dihadapkan pada persoalan berbeda.
Sebagai bangsa yang berdaulat, bangsa Indonesia yang diproklamirkan 17 Agustus 1945 oleh “Founding Fathers” kita, memerlukan sebuah identitas untuk dapat maju menjadi bangsa yang berkembang. Pada masa awal-awal kemerdekaan, identitas kebangsaan bergulat seputar antara “Kami bangsa yang pernah dijajah, dan kamu bangsa yang pernah menjajah”. Romantika kebangsaan ini masih sering diangkat dalam berbagai kesempatan saat-saat ini. Jargon-jargon seperti “Merdeka!” masih saja dikumandangkan oleh beberapa politikus. Sayangnya romantika ini mengalami pendangkalan makna dari generasi saat ini yang sudah mengalami keterpisahan jauh dari perjuangan perebutan kemerdekaan dahulu kala. Untuk itu kita memerlukan suatu konteks kebangsaan yang baru, yang membuat kalbu bergetar saat kita mengucapkan: “Aku orang Indonesia!”, atau “Gue anak Indonesia!”
Garuda di Dadaku dan KeIndonesiaan
“Garuda di Dadaku (GDD)” adalah film keluarga yang berkisah tentang bagaimana seorang anak bernama Bayu yang berjuang untuk menjadi pemain bola meskipun dilarang oleh kakeknya. Bayu berusaha berbohong menutupi aktifitasnya berlatih bola untuk dapat masuk ke tim nasional usia 13. Kakeknya melarang Bayu bukan tanpa sebab, tapi karena trauma ayah Bayu yang ingin jadi pemain bola namun berakhir cedera dan miskin hingga akhirnya meninggal dalam sebuah kecelakaan tragis. Yang saya ingin angkat disini bukan jalan cerita film ini, tapi fenomena yang terjadi di antara penonton (yang pada saat tulisan ini dibuat telah mencapai angka satu juta penonton bioskop). Lewat media facebook yang trend, film GDD berhasil memanfaatkan jejaring sosial untuk menangkap kesan dan pesan dari penontonnya. Dari 50.000 lebih fans di facebook, banyak dari mereka menuliskan kesan dan pesannya. Kebanyakan dari mereka (yang sebagian besar anak-anak) tersentuh emosinya dan bangga menjadi bangsa Indonesia. Film ini telah menggelitik rasa nasionalisme penontonnya dan perasaan ‘Gue orang Indonesia’ tiba-tiba merasuk kalbu, seiring dengan rasa simpati perjuangan Bayu masuk tim nasional. Penonton bersorak, bertepuk tangan dalam gedung bioskop layaknya di stadion mendukung tim nasional (rasanya jarang fenomena seperti ini ada di gedung bioskop nasional).
Apa yang dapat kita simak di sini? Film ini berhasil memindahkan fenomena “Gue orang Indonesia” yang ada di stadion bola – yang mungkin banyak keluarga Indonesia tidak pernah ada di sana – dan memindahkannya ke dalam gedung bioskop. Film ini dapat menjadi investasi semangat untuk mewujudkan tim sepakbola yang lebih baik di masa depan, layaknya film kartun kapten Tsubasa, (sebuah film tentang sepabola) yang diyakini sebagai embrio sepakbola Jepang yang bergengsi di tingkat Asia dan dunia satu dekade kemudian. Saya harap demikian. Bukan hanya di dunia olahraga, tapi juga di bidang-bidang lainnya.
Garuda dan Indonesia
Kebetulan film GDD ini materi promosinya didesain oleh penulis dan tim. Ketika diminta mendesain tampilan visual untuk poster dan turunan materi promosinya, kami mulai mencari referensi seputar garuda, film tentang garuda, sepakbola, dsb. Salah satu studi yang dilakukan sebelum membuat tampilan visualnya, kami melakukan ‘desktop research’ untuk kata-kata kunci tadi. Ketika kami mengetikkan kata ‘garuda’ di Google, situs yang keluar pertama di layar komputer adalah Garuda Indonesia. “Wah hebat juga “, pikir saya. Kata Garuda punya brand awareness yang dimiliki bangsa Indonesia. Ketika mencari dengan keyword ‘Garuda movie’ didapati juga film monster Garuda dari Thailand.
Garuda adalah burung mitologi dalam kebudayaan Hindu Budha (sama seperti Sri Rama di atas). Garuda digunakan menjadi simbol di banyak negara seperi India, Mongol, Thailand. Meskipun bukan budaya yang lahir di tanah Indonesia, Garuda telah menjadi simbol visual kebanggaan bangsa Indonesia. Terima kasih kepada Sultan Hamid II dan Presiden Soekarno yang memiliki rasa estetika yang baik, dalam menggambar Garuda berbeda dari garuda lainnya di dunia. Garuda di Indonesia juga sudah mengalami ‘positioning’ baru, bukan lagi garuda biasa tapi ‘Garuda Pancasila’. Inilah garuda khas Indonesia. Untung juga kita juga punya penerbangan dengan nama Garuda Indonesia yang berperan besar mem ‘branding’ kata garuda, menjadi milik bangsa Indonesia. Disini kita melihat, kadang identitas kebudayaan memerlukan komunikasi kebudayaan yang baik untuk menjadi milik suatu bangsa (yang dapat dipersamakan dengan konsep branding untuk suatu produk atau jasa). Jadi seringkali kebudayaan bukanlah soal orisinalitas dan tidak, tapi juga soal siapa yang mengkomunikasikannya secara ‘massive’. Sama seperti produk hamburger yang menjadi khas Amerika (karena ada raksasa penjaja hamburger Mc Donalds) meskipun hamburger konon berasal dari nama sebuah kota pelabuhan di Jerman, Hamburg. Jadi dalam kasus Reog atau Batik atau apapun yang di klaim malaysia milik mereka, mungkin kita sebelumnya kurang berkoar-koar kepada dunia bahwa kesenian tersebut adalah milik kita.
Konsep Brand of Indonesia sebagai Identitas Indonesia
Saya pernah mengikuti diskusi tentang konsep Brand of Indonesia yang diadakan salah satu pembicara terkemuka. Sayangnya pembicaraan diskusi tadi akhirnya hanya sebatas diskusi seputar tagline yang cocok dibuat untuk Brand of Indonesia. Ibarat mau meluncurkan produk, belum tahu produknya apa, sudah mau dibuat iklannya. Konsep saya tentang brand tetap sama: brand adalah pengalaman (experience) yang dibangun lewat berbagai strategi. Tanpa kita membangun experience-nya, Brand of Indonesia hanya sebatas logo dan tagline. Pertanyaannya adalah apa dan bagaimana Brand of Indonesia? Kalau brand diartikan identitas, identitas apa yang sanggup mewakili seluruh tumpah darah Indonesia?
Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan berbagai suku bangsa di dalamnya (konon lebih dari 300 suku). Dengan keragaman yang terbentang di dalamnya, sulit sekali menentukan kekhasan budaya yang umum, yang mewakili semua suku bangsa Indonesia. Polemik kebudayaan kerap dipertanyakan dalam berbagai kesempatan – seperti dipertanyakan di awal tulisan ini.
Untuk menjawab pertanyaan di atas tadi – bagaimana membuat generasi penerus mempunyai ‘identitas’ nasional – semestinya kita tidak terburu-buru menjawabnya dengan sikap hanya sekedar mencekoki pemakaian ‘atribut-atribut’ tradisional yang kita cap selama ini sebagai identitas kita. Karena jika demikian, pasti ada jurang kebudayaan antara jiwa kekinian dan masa lalu sehingga mungkin akan segera menjadi tidak relevan. Tapi yang esensial adalah semangat untuk berbeda, menjadi ‘seseorang’ di antara bangsa-bangsa dunia. Jadi ibaratnya adalah, jika saya memakai batik, bukan karena persoalan batik adalah Indonesia, tapi karena saya mau berbeda dengan yang memakai setelan jas, dan saya adalah orang Indonesia. Jadi jika polanya dibalik: ketika semua orang pakai batik, saya akan memakai setelan jas, dan saya tetap orang Indonesia! Itulah pola mentalitas yang perlu kita investasikan di dalam generasi muda! Wawasan yang sempit bahwa kebudayaan harus lahir sebagai suatu peninggalan lama, yang diwariskan turun temurun, dan orisinal dari dahulunya, seringkali membuat kebudayaan kita tidak bisa berkembang. Kebudayaan sering dilihat sebagai benda utuh yang sudah jadi, yang diberikan orang tua kita, yang tidak boleh diapa-apakan. Sebaliknya kita seharusnya melihat budaya yang ada sebagai modal yang dapat dikembangkan, dibangun, dibongkar, disempurnakan. Ibarat permainan lego, kita dapat membentuk bentuk baru, pola baru, dari elemen-elemen yang sudah ada sebelumnya. Elemen-elemen ini adalah kedalaman nilai, pemikiran mendalam, yang disebut sebagai nilai-nilai luhur. Dengan demikian kita tidak terjebak di permukaan pada yang kelihatan saja, tapi dapat memaknai setiap elemennya dalam keseharian kita.
Peran Agen Kebudayaan dan Legitimator Kebudayaan
Dalam sebuah kebudayaan selalu ada yang disebut sebagai agen kebudayaan. Agen kebudayaan adalah pioner, orang-orang kreatif, inspiratif dan berpengaruh dalam meletakkan suatu paham, pola atau konsep tertentu kepada masyarakat. Dalam konteks kebudayaan yang dibatasi pada karya seni dan desain juga demikian. Dahulu ada empu yang membuat model senjata berlekuk, ditiru komunitasnya, menyebar, dan diwariskan turun temurun disebut keris. Dahulu ada yang membuat batik dengan gambar tertentu, diadaptasi di suatu daerah, jadilah batik itu menjadi khas suatu daerah. Apakah agen kebudayaan dalam karya seni dan desain sudah tidak ada di jaman ini? Saya rasa akan selalu ada. Kita ambil contoh F. Widayanto yang keramiknya begitu khas dan unik. Ditiru banyak pengrajin keramik seantero Indonesia. Untunglah Mas Widayanto berbesar hati tidak mau menuntut HAKI pengrajin-pengrajin plagiat ini. Kalau sudah menyebar seperti ini semestinya tinggal dikomunikasikan secara propaganda strategis, bahwa inilah keramik Indonesia! Jadilah sebuah brand: Ceramic of Indonesia!
Semasa jaman kerajaan dahulu, legitimator kebudayaan berpusat di dalam istana/keraton. Raja atau istana adalah orang atau lembaga yang berdaulat menentukan estetika dan melegitimasi mana yang menjadi seni tinggi (istana) dan seni rendah (rakyat). Setelah jaman kemerdekaan, tiba-tiba legitimator ini hilang seiring meleburnya kekuasaan kerajaan ke dalam pemerintahan berdaulat. Sayangnya pemberi cap ini juga tidak serta merta langsung dapat dijalankan oleh pemerintah secara aktif. Akibatnya tidak ada lagi kesenian yang diciptakan dan di beri brand sebagai kebudayaan nasional. Contohnya dalam seni tari. Tari-tarian baru yang diberi cap tari nasional atau setidaknya tari daerah seolah tidak pernah ada lagi. Penciptaan tari saat ini menjadi lebih kontemporer, sporadis, sebagai bagian budaya pop, yang ada dan kemudian mati. Sedangkan yang lama, yang sudah ada turun temurunlah yang dianggap lebih ‘sah’ mewakili Indonesia. Padahal yang lama pun saat diciptakan adalah sebuah budaya yang baru. Tapi seiring waktu, dipentaskan secara terus menerus, diakui keberadaannya sebagai milik suatu kelompok, mendarah daging dan bukan milik orang lain. Inilah betapa ’sense of belonging’ juga merupakan peranan yang penting dalam mencari identitas kebangsaan. Rasa memiliki merupakan modal sebuah identitas.
Saya kadang berpikir mengapa tidak mencap gaya ‘ngebor’ Inul sebagai salah satu tarian the Brand of Indonesia? Saya pikir cukup orisinal, tidak ditemukan dimana-mana, dapat dibandingkan dengan originalitas gaya ‘moonwalker’ mendiang Michael Jackson. Inul pun menginspirasi banyak gaya-gaya baru sejenis seperti: kayang, goyang patah-patah, dsb. dalam dunia dangdut Indonesia. Tapi kembali lagi, masalahnya apakah gaya ini bisa diterima di berbagai kalangan. Ini hanya sebuah contoh ekstrim dari penulis. Poin yang saya ingin bagikan adalah perlu legitimasi dari pihak yang dominan – dalam hal ini mungkin peran pemerintah yang paling tepat – untuk membuat ‘cap-cap baru’ ‘Brand of Indonesia’ (seperti dahulu pernah diciptakannya ‘cap’ batik sebagai baju nasional untuk pegawai negri di seluruh Indonesia).
Untuk itu isu perlunya Departemen Kebudayaan yang terpisah dari Departemen Pariwisata cukup relevan didiskusikan keberadaannya. Kebudayaan harus menjadi pembentuk identitas bangsa, bukan hanya sebatas kendaraan kepentingan pariwisata seperti yang ada selama ini. Departemen ini juga bisa menjadi pusat propaganda baik secara nasional maupun global untuk hal-hal yang dianggap ‘sah’ mewakili identitas Indonesia. Kalau saja propaganda ini tercipta dengan baik, maka ‘claim’ dari pihak manapun terhadap identitas kita– seperti terjadi dari pihak negeri tetangga kita baru-baru ini – tidak perlu diresahkan. Mari kita tantang beradu propaganda!
‘Sub Brand of Indonesia’ Mengapa Tidak?
Seorang sahabat, Andi S Boediman pernah mengusulkan Brand of Indonesia dimulai dari bentuk yang sifatnya kedaerahan, untuk memudahkan pembentukannya. Kalau dari terminologi brand adalah membentuk sub brand-nya dahulu, baru dari sub-sub yang ada akan terbentuk identitas ‘parent brand-nya’. Untuk legitimatornya dibentuk badan seperti layaknya ISO yang mengawasi kualitas mutu dan standar hasil budaya. Legitimator ini akan memberi cap “Product of Bandung, Product of Bali, Product of Jogja”, dsb. Dengan demikian kualitas yang berkesinambungan dapat dijaga. Ide ini juga mungkin bisa menjawab keadaan kualitas produk industri Indonesia yang kadang masih seadanya. Ide ini dapat juga memupuk rasa kebanggan atas daerahnya tanpa terjebak pada rasa primordial yang sempit. Meskipun konsep ‘sub brand Indonesia’ ini baik untuk dilakukan lewat swadaya masyarakta setempat, namun tetap saja, sebagai negara besar Indonesia memerlukan konteks kepemilikan bersama seperti dibahas di atas tadi. Untuk itu peran pemerintah tetap sangat dibutuhkan.
Akhir kata
Tulisan ini memang tidak menjawab secara pasti apakah Brand of Indonesia, tapi hanya menyoroti mentalitas yang dapat kita tempuh untuk mencapainya. Tampaknya kita harus tetap bersabar, bekerja keras, tetap mempertanyakan, tetap mencari, sampai suatu hari menemukannya. Rasa ingin menjadi sesuatu, berbeda dengan bangsa lain, tapi memiliki kesamaan, kebersamaan, tenggang rasa, dan saling menghormati, dan saling memiliki dengan sesama bangsa harus terus dicari dan diciptakan dalam berbagai kesempatan. Ini adalah modal dasar investasi kita untuk “The Brand Called INDONESIA”.
•••
http://desaingrafisindonesia.wordpress.com/2009/08/25/investasi-menuju-“the-brand-called-indonesia”/